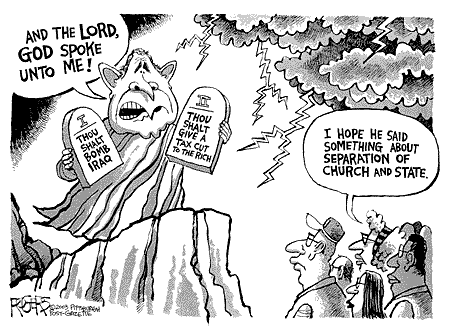Indonesia secara konstitusional mengidealkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang latar belakang status, suku, ras, termasuk agamanya. Konstitusi dasar negara ini telah menjamin tiap-tiap warga negara untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.
AGAMA, DI INDONESIA, tentu saja sudah hadir jauh sebelum Negara Kesatuan Republik ini resmi didirikan. Di nusantara, jumlah agama tak terbilang, sepadan banyaknya dengan ragam nusa, etnik, dan budaya bangsa ini. Ada yang tumbuh dari tanah air sendiri, ada pula yang bermigrasi dari negeri seberang. Kesemuanya serempak hidup bersama dalam semarak kebhinekaan sepanjang sejarah kehidupan bangsa. Semangat bhineka tunggal ika menjadi fondasi yang kukuh bagi bertumbuh-kembangnya beragam aspirasi dan ekspresi warga negara, termasuk dalam hal beragama.
Keniscayaan pluralitas agama itu disadari betul oleh para founding persons sejak mula pertama mereka mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Karena itu, sejak awal mereka mengukuhkan undang-undang yang menjamin keberlangsungan hidup agama-agama itu, dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk dan mengamalkan agama sesuai dengan pilihan nuraninya. Sejak semula negara ini dibangun berdasarkan undang-undang yang menjamin terciptanya keadilan dan perlindungan bagi semua agama yang hidup di rumah kediamannya. Indonesia tidak mendasarkan peraturan perundang-undangannya pada satu agama tertentu atau juga pada semua agama yang ada. Meski begitu, Indonesia mengakui bahwa agama-agama telah memberikan inspirasi, spirit, dan nilai-nilai bagi pembentukan undang-undang dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tapi apa mau dikata, pada kenyataannya kita masih belum hidup dalam kondisi “yang semestinya” sebagaimana dicita-citakan konstitusi asali negeri ini. Idealitas seringkali selalu tak sepenuhnya sejalan dengan realitas. Visi undang-undang seakan terkungkung dalam teks belaka, dan seolah tak jua terjangkau oleh ikhtiar yang sepanjang sejarah telah dan terus diupayakan. Realitas belakangan ini menampilkan banyak indikator bahwa kemerdekaan beragama di Indonesia masih jauh dari harapan. Sebagian dari kita seakan belum memiliki kesadaran penuh untuk menerima secara lugas adanya kemajemukan corak dan model keberagamaan yang hadir di dalam bangsa ini. Sebagian masyarakat kita masih bersikeras memaksakan kehendak untuk melakukan dominasi dan subordinasi atas paham keagamaan yang berbeda darinya.
Berbagai kasus kekerasan dan konflik horisontal atas nama agama, yang di era reformasi ini kembali menggelora, mencederai spirit ideal yang dicita-citakan para pendahulu negeri ini. Ironisnya, aparatus negara ikut tergerus arus, bahkan menjadi pion pelanggar rambu-rambu universal yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar. Berbagai turunan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dari sejak orde lama hingga orde reformasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak sedikit yang justru berseberangan dengan undang-undang dasar. Produksi peraturan pemerintah tidak sedikit yang kemudian dimanfaatkan menjadi instrumen bagi pihak tertentu untuk menyerang pihak lain yang berbeda iman, baik dalam kelompok agama yang sama maupun antar agama yang berbeda. Bahkan, seringkali peraturan itu dilatarbelakangi oleh desakan dan tekanan dari kelompok tertentu yang kebetulan vokal dan punya energi berlebih untuk dapat mengakses titik-titik lemah hukum dan kekuasaan.
Pasca reformasi, tak terbilang sudah kasus kekerasan, intoleransi, dan konflik atas nama agama yang berjuta kali menjadi headline media massa. Sebut saja –sebagai misal– Al-Qiyadah, Lia Eden, Jemaat HKBP, Pesantren Khilafiyah Umar Thalib, Tragedi Temanggung, dan lain-lain. Atau yang paling kuat terekam dalam ingatan, yakni kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang bertubi-tubi dihakimi massa di sana-sini. Mereka kehilangan nyawa, kehilangan rumah, kehilangan tempat ibadah, kehilangan mata pencaharian, serta kehilangan rasa aman. Cikeusik menjadi saksi terakhir penghakiman yang mereka derita. Ironisnya, pemerintah yang menjadi tumpuan harapan dan perlindungan, belakangan malah melarang mereka untuk mereguk kemerdekaan dalam menjalankan keyakinan mereka. Atas nama stabilitas dan kehendak mayoritas, mereka dikucilkan dan dipenjarakan di bumi dimana mereka dilahirkan. Mereka dikerangkeng oleh SKB dan Peraturan Daerah, tanpa proses pengadilan yang selayaknya. Bagaimana nasib mereka hari ini, masihlah belum jelas benar keadaannya.
Negara agama atau negara sekuler?
Indonesia, dalam upaya menata regulasi atas pluralitas agama yang dianut warga negaranya, seakan terlilit dalam dilema tarik ulur wacana dan retorika antara menjadi negara agama atau menjadi negara sekuler. Sejauh ini, negeri kita seakan belum menemukan formulasi yang tepat bagaimana membangun relasi ideal antara negara dengan agama. Bahkan sesungguhnya, sejak awal perumusan dasar negara pada sidang-sidang BPOPKI, para founding persons bangsa ini sudah memperdebatkan perihal itu, termasuk kasus “7 kata” yang sampai hari ini masih sensi untuk diperbincangkan. Kita dapat mengkaji dinamika perdebatan itu melalui rekaman para ahli sejarah, tentu saja dalam sekian versi sesuai dengan sudut pandang dan wawasan pengetahuan masing-masing.
Dalam konteks relasi negara dan agama, negara-negara Barat dan Eropa yang sebagian besar menganut demokrasi liberal, diyakini cukup berhasil melakukan harmonisasi hubungan antara keduanya melalui proses sekularisasi. Dalam hal ini, sekularisasi dimaknai sebagai penempatan secara proporsional hubungan antara agama [sebagai entitas yang bersifat private-sacred] dengan negara [sebagai entitas yang bersifat publics-profane]. Secara teoretis, ada tiga prinsip dasar negara sekuler, yakni pemisahan negara dan agama, kebebasan beragama, dan netralitas negara. Ketiga prinsip ini meniscayakan adanya jaminan bahwa negara sama sekali tidak mencampuri urusan agama sepanjang tidak berkenaan dengan ranah publik kehidupan para pemeluknya. Negara harus mengambil jarak yang sama terhadap setiap agama yang ada. Sebaliknya, sebagaimana halnya negara tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dan agama, maka agama pun tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dengan negara.
Prinsip pertama sekularisasi hubungan antara negara dan agama mengasumsikan bahwa negara tidak diperkenankan memfasilitasi lembaga-lembaga agama, tidak diperkenankan menggunakan pejabat lembaga agama untuk menjalankan pekerjaan negara, dan tidak punya kekuasaan untuk menunjuk pejabat atau menentukan aturan internal dari lembaga-lembaga agama. Prinsip kedua menekankan pada kemerdekaan setiap warga negara untuk mengimani dan mengamalkan agama yang diinginkannya, mengubah keyakinannya, atau bahkan tak beragama sekalipun. Dalam posisi ini, negara tidak memiliki kewenangan untuk menghalang-halangi dan melakukan intervensi dalam hubungan individu dengan keyakinan religiusnya. Prinsip ketiga meniscayakan negara untuk tidak membeda-bedakan warga negara atas dasar keyakinan religiusnya. Hukum negara berlaku adil bagi semua warga, apapun agamanya.
Akan tetapi, tampaknya sampai saat ini belum ada negara yang sepenuhnya cocok dengan model ideal semacam di atas. Bahkan negara Inggris atau Amerika Serikat sekalipun, yang disebut-sebut sebagai negara sekuler itu, belum sepenuhnya dapat memutus hubungan secara sungguh-sungguh dengan institusi atau pengaruh agama, terutama agama yang berpemeluk mayoritas. Inggris, dalam beberapa hal ketatanegaraan, masih bersinergi dengan Gereja Anglikan. Pejabat Gereja Anglikan sampai sekarang ini, misalnya, masih ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris. Di Amerika, meski di tingkat nasional menggunakan paradigma hukum sekuler, tetapi belum juga dapat melakukan sinkronisasi regulasi atas sebagian negara bagiannya yang memiliki kewenangan untuk menyusun hukumnya sendiri mengenai agama. Bahkan sebagian negara bagiannya masih menggunakan uang pajak untuk membiayai lembaga-lembaga agama. Belum lagi pengaruh kuat sekte agama tertentu kepada para pejabat negaranya, yang kebetulan menganut sekte agama itu. Terlebih, politik luar negeri Amerika yang masih dinilai unfair terhadap negara-negara tertentu yang berbasis agama –dalam hal ini Islam, menyisakan tanda tanya besar atas paham sekuler yang dianutnya itu.
Indonesia sendiri, menurut sebagian kalangan, pada umumnya sudah juga menerapkan prinsip negara sekuler seperti di atas. Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila (1984), Indonesia disebut sebagai “negara sekelur yang tidak sekularistik”. Dalam buku itu disebutkan adanya tiga macam negara sekuler. Pertama, negara sekuler yang anti agama. Kedua, negara sekuler yang netral terhadap agama. Ketiga, negara sekuler yang menghargai agama. Indonesia, menurut buku itu, masuk dalam kategori ketiga. Di masa orde baru, muncul wacana yang mendefiniskan Indonesia sebagai “bukan negara agama dan bukan negara sekuler”. Wacana ini mengasumsikan bahwa Indonesia tidak bisa disebut sebagai “bukan negara agama”, karena secara tekstual-konstitusional negara ini “berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebaliknya, Indonesia tidak juga bisa disebut sebagai ”bukan negara sekuler” oleh karena alasan yang sama.Di tempat lain, Indonesia disebut-sebut sebagai “negara theis demokratis”, yang berarti negara yang berketuhanan, tetapi tidak berdasarkan agama.
Tetapi, anggapan seperti di atas tampaknya perlu untuk terus-menerus dipertanyakan ulang. Pertanyaan utamanya antara lain terkait dengan dua hal, yakni problem institusionalisasi agama dalam struktur negara dan domain area peran serta fungsi negara bagi agama-agama. Soal eksistensi Kementerian Agama, misalnya, menjadi unsur sangat signifikan bagi poin penting pertanyaan itu. Sebab, kementerian yang sedianya menjadi wadah aspirasi bagi seluruh agama yang ada itu, sebagai satu misal, seakan masih terkungkung pada urusan beberapa agama yang dianggap sebagai “agama resmi negara” belaka. Belum lagi jika kita menelisik lebih jauh pada pernak-pernik persoalan di level yang langsung bersentuhan dengan hak warga negara. Persoalan kolom agama di KTP, misalnya, menyisakan ruang konflik bagi banyak pemeluk agama, terlebih bagi para pemeluk “agama yang tak terakui”. Turunannya adalah berbagai kasus dalam hal perkawinan, akta lahir, kartu keluarga, dan sederet kasus lainnya yang terkait erat dengan pemenuhan hak sipil para penganut “agama yang tak terakui” itu.
Terminologi Salah Kaprah
Sejak dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965, secara tak sadar benak aparatur negara dan rakyat seakan tergiring dalam pola pikir dualistik dalam hal mendefinisikan status agama-agama. Lantas lahir pula Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 tanggal 18 November 1978 yang seakan semakin menegaskan pola pikir itu. Di kemudian hari, kedua peraturan itu menebalkan persepsi dan perilaku diskriminatif negara atas agama-agama yang ada. Dari kedua peraturan inilah, secara tak sadar, menyeruak paham mengenai adanya “agama resmi” dan “agama tak resmi”. Legitimitas “agama resmi” itu semakin menguat manakala berbagai aturan administrasi kependudukan membatasi sebagian pemeluk agama yang secara kebetulan –atau barangkali sengaja– tak disebutkan secara harfiah dalam uraian penjelasan daripada peraturan-peraturan itu. Terminologi itu belakangan hari melahirkan berbagai derivasi kebijakan yang tak adil terhadap banyak agama yang tak terakomodir secara implisit dalam teks peraturan itu.
Selain termin “resmi dan tak resmi”, distingsi yang sangat kental tercermin pula pada penyebutan istilah antara “agama” dengan “aliran kepercayaan” dalam teks peraturan perundang-undangan kita. Termin ini seolah mendefinisikan “aliran kepercayaan” sebagai “sesuatu yang lain yang bukan agama”. Agama-agama lokal yang tumbuh dan berkembang dalam etnis-budaya masyarakat, seperti halnya Sunda Wiwitan, Sapta Darma, Kaharingan, Samin, Honggodento, Subud, dan lain-lain, dikategorikan sebagai hanya “aliran kepercayaan” atau “aliran kebatinan” itu. Lebih parahnya lagi, pada ranah praksis “aliran kepercayaan” itu tidak masuk dalam domain Kementerian Agama, melainkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, seperti misalnya yang terjadi pada Sapta Darma.
Terminologi salah kaprah di atas menyisakan soal besar berupa reduksi dan distorsi atas interpretasi negara atas agama, sekaligus juga interpretasi penganut agama atas agama yang dianutnya dan agama lain yang tidak dianutnya. Dan dalam hal ini, negara berperan besar dalam menanam dan menyemai hegemoni tafsir yang keliru atas definisi dan status agama-agama itu. Dalam realitasnya, terminologi ini meniscayakan adanya penafian terstruktur atas berbagai agama lokal dan agama minoritas yang hidup di Indonesia. Implikasinya adalah terciptanya proses tirani, dominasi, dan subordinasi antara negara terhadap agama tertentu, dan antara satu agama [yang mayoritas] terhadap agama lain [yang minoritas].
Contoh faktual yang sering menjadi sorotan dari kesalahkaprahan di atas adalah soal pengisian kolom agama di KTP. Para penganut agama selain lima “agama resmi”, yang sejak era Gus Dur bertambah satu menjadi enam, sampai saat ini masih tidak gampang mendapatkan legitimasi kewarganegaraannya. Padahal, KTP adalah syarat mutlak bagi pemenuhan hak kewarganegaraannya itu. Implikasinya tentu saja hak-hak sipil yang seharusnya mereka dapatkan itu menjadi sirna. Sebenarnya, Keppres No. 6 Tahun 2000 telah mencabut Surat Edaran Mendagri tahun 1978 itu, dan memberi peluang bagi agama-agama “minoritas” untuk tampil sejajar dengan agama lainnya. Keppres ini diperkuat oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006 yang juga bernada sama. Akan tetapi, proses sosialisasi peraturan baru itu masih belum banyak tergarap, karena tidak adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang memadai bagi terselenggaranya kebijakan itu.
Idealisasi dan Harmonisasi
Pengelolaan hubungan antara negara dan agama bisa dibangun atas dasar saling kontrol dan saling mengimbangi. Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk bersifat tiranik dan hegemonik, yang bermuara pada sikap represif, koruptif dan eksploitatif terhadap warga negaranya, musti dikontrol dan diimbagi oleh spirit agama-agama yang mengutamakan rahmatan lil ‘alamin. Kontribusi agama-agama dengan kekayaan nilai-nilai etika dan moralnya sangatlah diperlukan bagi persemaian nilai-nilai kenegarawanan. Sentuhan etika Kristen dengan basis kasihnya, etika Hindu dengan semangat ahimsanya; etika Budhis dengan etos kesederhanaannya, etika Islam dengan spirit keadilannya, dan spiritualitas agama-agama lainnya yang mengandung kebajikan dan kebijaksanaan, masih teramat relevan bagi pengawasan kebijakan negara. Kohesi sosial yang dibangun atas dasar spiritualitas agama-agama harus menjadi salah satu benteng yang kokoh manakala negara abai terhadap kewajiban yang mesti dipenuhinya. Hukum positif negara juga sangat mungkin bersumber dari hukum agama. Tentu saja proses adopsinya musti melalui prosedur dan persyaratan tertentu. Sebagai misal, hukum agama yang diadopsi itu secara substansial beroreintasi pada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Secara prosedural, sumber hukum itu harus diterima oleh nalar publik melalui proses penetapan hukum secara demokratis. Hukum apapun yang memenuhi syarat minimal ini memiliki hak dalam mengisi bangunan hukum positif dan perundang-undangan negara.
Di sisi sebaliknya, dalam konteks penataan kebijakan publik, negara mesti berperan dalam pengawasan atas kemungkinan penyalahgunaan agama sebagai sumber dominasi dan otoritarianisme antara satu agama terhadap agama yang lainnya. Sepanjang berkenaan dengan ranah publik hubungan antar warga negara, yang kebetulan memeluk agama atau keimanan yang berbeda, negara berkewajiban memberikan regulasi dan demokratisasi yang setimbang dan berkeadilan. Kewajiban pelayanan negara dalam konteks hajat hidup keberagamaan rakyatnya haruslah sepadan layaknya ketika ia melayani hajat hidup rakyat lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain-lain.
Indonesia secara konstitusional mengidealkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang latar belakang status, suku, ras, termasuk agamanya. Konstitusi dasar negara ini telah menjamin tiap-tiap warga negara untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Jaminan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara itu menjadi syarat mutlak bagi negara dalam menjalin relasi harmonis dengan institusi agama dan para pemeluknya. Hidup bersama dan bekerja sama antar pemeluk agama harus menjadi spirit ideal dalam dinamika sejarah kehidupan bangsa. Dengan demikian, pengakuan eksistensial atas agama-agama dan ekspresi keimanan yang selama ini terpinggirkan, bukan didorong oleh karena “kebaikan hati” atau berkat pemberian dari yang mengklaim diri sebagai “yang mayoritas dan dominan”. Pengakuan itu harus bermula dari kesadaran bahwa setiap pemeluk agama dan penganut keimanan yang berbeda dengannya, adalah sama-sama warga negara yang hajat hidupnya dijamin oleh konstitusi, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rumah demokrasi, yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia.[]
Dimuat dalam Majalah Suluh Edisi 53 Tahun 2011